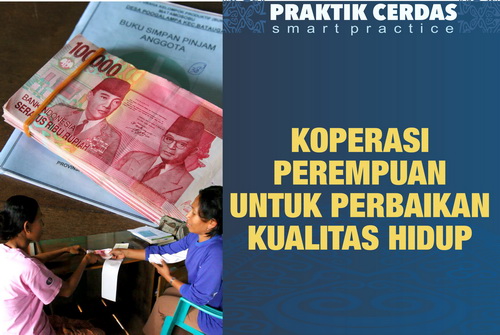“Berulang kali saya diminta membuktikan cinta saya tapi selalu saya tolak. Mungkin saat itu saya lemah tapi hanya sekali itu saja saya tak kuasa menolak permintaannya. Sekarang saya hamil dan dia jadi suka marah dan memukul. Saya harus bagaimana, mak?”, Bunga, gadis belasan tahun itu menyeka air mata yang mengalir di pipinya.
Sarci Maukari mendengarkan dengan seksama penuturan Bunga. Sebagai seorang konselor bagi korban kekerasan terhadap perempuan , Sarci memang harus selalu siap kapan saja mendengarkan curahan hati mereka yang memberanikan diri mendatangi kantor Sanggar Suara Perempuan untuk mendapatkan perlindungan. “Bagi saya, ini panggilan hidup, betapa pun beratnya perlawanan yang saya hadapi dari pihak pasangan klien dan pandangan merendahkan dari segelintir masyarakat”, Sarci yang juga ibu dari dua orang anak ini menjelaskan kenapa dirinya tetap bersemangat dalam mendampingi para klien Sanggar Suara Perempuan.
Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, kaum perempuan di Soe, Kupang, dan banyak daerah lain di Nusa Tenggara Timur, tidak punya pilihan selain diam menerima perlakuan kasar. Segala bentuk kekerasan, akan selalu tertutup rapat kisah ini dan terkubur dalam-dalam agar tak menjadi aib bagi keluarga besar. Desa-desa yang kering di Nusa Tenggara Timur menjadi lebih gersang tanpa senyum para ibu.
Seratus kilometer dari Soe, di Penfui Timur Kabupaten Kupang, Venty Sabaat mengenang kondisi masa lalu kaum perempuan di desanya. “Dahulu banyak sekali masalah yang kami hadapi. Uang tak pernah cukup untuk membeli makanan, anak-anak sakit, suami selingkuh”. Ibu berumur 43 tahun ini sadar betul, perempuan-perempuan di desanya merasa malu dan takut bila ada yang tau mereka diperlakukan kasar. “Karena punya banyak anak, banyak ibu diam di rumah saja, sering murung, gampang marah, sering bertengkar dan dipukuli suami”, tuturnya.
Kondisi yang dihadapi Bunga, Venty Sabaat, dan banyak perempuan lain di bumi Timor ini mendorong Sanggar Suara Perempuan sejak tahun 1996 memfokuskan pekerjaan mereka pada upaya menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan. Saat itu belum ada organisasi masyarakat maupun instansi pemerintah yang perduli akan permasalahan ini. Kerap kali mereka dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang dan dipandang sebelah mata karena mau mengurusi perempuan-perempuan yang dianggap telah melakukan aib atau membuka aib keluarga. Namun cemoohan masyarakat saat itu tidak menyurutkan semangat mereka.
Kegiatan penyadaran perlahan mendapat dukungan masyarakat. Pada tahun 2002, Sanggar Suara Perempuan mendirikan Rumah Perempuan yang menjadi tempat perlindungan bagi para perempuan korban kekerasan di Kota Kupang. Ini memperluas wilayah kerja Sanggar Suara Perempuan yang sebelumnya hanya tiga puluh kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, menjadi empat puluh kecamatan termasuk sepuluh kecamatan lagi di Kabupaten Kupang dan kota Kupang.
Pengalaman berjuang sendiri selama lebih sepuluh tahun, membuat Sanggar Suara Perempuan dan Rumah Perempuan lebih terbuka terhadap berbagai inisiiatif dari institusi lain yang mengurusi hal yang sama. “Sanggar Suara Perempuan dan Rumah Perempuan tidak segan berbagi rahasia sukses agar yang lain dapat mereplikasinya. Kami dapat saling belajar dan melakukan berbagai inisiatif bersama, seperti layanan pendampingan hukum korban kekerasan terhadap perempuan yang terintegrasi, antara Biro Pemberdayaan Perempuan, Pengadilan Tinggi, Kepolisian, dan LSM”, tutur dr. Yovita A. Mitak, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi NTT.
Hingga saat ini Sanggar Suara Perempuan di kota Soe telah mendampingi 987 kasus dan Rumah Perempuan di kota Kupang mendampingi 1329 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, ingkar janji menikah, dan traffiking. “Kami yakin jumlah kekerasan terhadap perempuan ini jauh lebih banyak daripada yang telah berhasil kami tangani karena masih banyak perempuan korban kekerasan yang belum berani melaporkannya” , jelas Filpin Therik, Wakil Direktur Sanggar Suara Perempuan.
“Dari seluruh kasus yang kami tangani, tantangan terbesar bagi kami adalah kasus-kasus darurat medis yang terjadi di pelosok pedesaan”, tutur Filpin Therik, Wakil Direktur Sanggar Suara Perempuan. Belajar dari pengalaman itu, Sanggar Suara Perempuan dan Rumah Perempuan membentuk gugus tugas di tingkat desa yang terdiri dari beberapa kader yang bekerja sebagai konselor dan paralegal di tingkat komunitas. “Keberadaan gugus tugas dan kader ini dapat memberi respon cepat atas laporan suatu kasus sekaligus terus menerus melakukan penyadaran dan mendorong perubahan perilaku kasar untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan”, ujar Filpin.
Banyaknya kasus yang telah berhasil ditangani oleh Sanggar Suara Perempuan dan Rumah Perempuan tidak membuat kedua lembaga ini berhenti berinovasi. Pada awal tahun 2009, Rumah Perempuan mereka melakukan sebuah pendekatan baru dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan, yakni melibatkan kaum pria.
“Ketika kami melakukan mediasi dengan pasangan klien, sangat sulit bagi mereka untuk bersikap terbuka kepada konselor kami yang semuanya perempuan”, ungkap Libby SinlaeLoE, Koordinator Rumah Perempuan di Kupang. “Suatu waktu, rekan aktivis yang laki-laki ikut mendampingi kami berdialog dengan pasangan klien. Keterlibatan mereka saat itu dapat mencairkan suasana yang sebelumnya kaku bahkan tegang. Pasangan klien dapat mengungkapkan lebih banyak hal dengan lebih rileks dan sebaliknya juga lebih terbuka menerima masukan-masukan”, kenang Libby.
Kejadian tersebut kemudian menginspirasi Rumah Perempuan untuk memulai program pendampingan bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dengan mulai merekrut konselor pria. “Saat ini telah ada tujuh konselor pria yang aktif mendampingi pasangan klien dalam memediasi kasus kekerasan terhadap perempuan”, tutur Libby bangga. “Kami yakin upaya ini dapat mengubah perilaku kasar pria terhadap perempuan. Pendekatan maskulin dalam upaya penyadaran ini juga dapat lebih cepat meluas di kalangan kaum pria. Jika evaluasi program ini pada akhir tahun nanti menunjukkan hasil yang baik, kami akan mengajak biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi NTT untuk melaksanakan inisiatif ini bersama”, ujar Libby optimis.
Tidak melulu berfokus pada pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan,Sanggar Suara Perempuan dan Rumah Perempuan juga berupaya menjangkau akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yakni kurangnya aktivitas ekonomi produktif dan terbatasnya wawasan tentang kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat.
Venty Sabaat dan ibu-ibu di Penfui Timur Kabupaten Kupang yang tergabung dalam Kelompok Rindu Sejahtera, kini bisa tersenyum karena dapat membantu perekonomian keluarga dari usaha menenun, menjahit, dan warung kecil di rumah mereka. Kelompok ini juga aktif mendorong para ibu mengikuti program keluarga berencana dan berkoordinasi dengan petugas Kecamatan untuk mengikuti program kontrasespi gratis. Mereka meyakini, dengan jumlah anak yang lebih sedikit, mereka punya lebih banyak waktu untuk melakukan kegiatan bermanfaat dan mengembangkan kapasitas diri.
Begitu pula dengan ibu-ibu dan remaja puteri di desa Kesetnana, Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang membentuk Kelompok Tani Oenunu sebagai wadah untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif, seperti menenun dan menyulam. Tempat pertemuan mereka juga menjadi pusat informasi kesehatan keluarga dimana pelayanan imunisasi bagi anak dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara rutin dilakukan.
“Mimpi saya, perempuan NTT bangkit dan menghasilkan karya-karya luar biasa yang memajukan daerah ini”, tutur Sarci Maukari dengan mata yang berbinar-binar. Sambil tersenyum Sarci berjalan meninggalkan gedung perkantoran Sanggar Suara Perempuan sore itu. Satu hari berlalu membawa satu langkah maju bagi masa depan perempuan Indonesia, penentu masa depan anak-anak, keluarga dan bangsanya.